Alfiyah Sudira ( Mahasiswi Pascasarjana, STFI Sadra)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “perempuan” berasal dari kata “empu”. Dalam Bahasa Jawa Kuno, yang kemudian diserap dalam Bahasa Melayu, yang berarti “tuan, mulia, hormat”. Kata empu tersebut mengalami pengimbuhan dengan penambahan “per-“ dan “-an” yang kemudian membentuk “perempuan”.
Dalam Bahasa Jawa, perempuan disebut wadon alias wadahe adon-adon, yang memiliki arti tempat dibentuknya sesuatu. Perempuan secara biologis bermakna orang yang mengalami menstruasi, memiliki rahim, hamil dan menyusui. Dengan pembawaan alaminya, pengalaman reproduksi perempuan sudah demikian kompleks dan bermacam rupa.
Sedikit flashback, tahun 2019-2021 adalah tahun yang cukup memberi saya banyak pelajaran berharga. Ya, dalam rentang waktu tersebut, saya “kebetulan” dipercaya menjadi pimpinan sebuah Organisasi kemahasiswaan tingkat Jakarta Selatan. Menjadi ketua itu berarti rela berkubang dalam salah. Satu menyukai, yang lain membenci. Saat segala sesuatunya lancar, tidak akan kita temui pujian. Namun saat ada celah, kitalah yang pertama dicerca. Menjadi ketua tidak semudah yang dikira, yang hanya bermodal telunjuk kemudian seluruh masalah reda. Kita harus rela berada pada posisi simalakama. Dipertaruhkan terus-menerus demi menjaga semuanya baik-baik saja. Pertarungan mental terjadi tak berkesudahan.
Seperti organisasi kemahasiswaan lainnya, organisasi yang saya pimpin memiliki visi misi yang lebih khusus mengenai keperempuanan, dan karena kekhususan itulah ia berstatus badan semi otonom dari organisasi induk, yang artinya semi independen. Independen, namun semi, “are you kidding me?” Ya, tetapi memang demikian adanya. Dalam segala hal, kami harus terus bersinergi dengan pimpinan laki-laki, yang dalam hal ini payung organisasi secara umum. Dalam kegiatan keorganisasian, kita harus selalu terlibat. Namun saat badan semi otonom kami memiliki agenda, yang biasanya identik dengan “keperempuanannya” para laki-laki ini enggan untuk terlibat, sebab mereka merasa itu adalah edukasi untuk para kaum hawa. Meskipun tidak dipungkiri pula, sesekali mereka turut membantu persiapan secara teknis. Namun, yang menjadi titik gelisah saya adalah lebih kepada kesadaran. Jika ada acara atau agenda yang pembahasan seputar tema-tema gender, kesetaraan, equity, emansipasi, feminisme, biasanya hanya digandrungi para perempuan, sangat sedikit laki-laki yang sadar bahwa mereka pun perlu untuk belajar. Sebab bagaimana akan membumikan kesetaraan, jika ghiroh sekadar ingin tahu saja timpang.
Berbicara tentang masa saya memimpin badan ini, tidak bisa lepas dari acara besar keorganisasian, salah satunya adalah konferensi tingkat provinsi. Masa konferensi tingkat provinsi adalah momen yang membekas. Sebab pada saat itu, yang seharusnya ketua/pimpinan itu bebas dari intervensi pihak manapun, namun tidak dengan saya. Mungkin hal ini juga dialami oleh pemimpin perempuan lainnya. Bahkan dalam halnya memilih, independensi kami terus digoyang. Hal-hal demikian terjadi menurut saya dikarenakan para perempuan belum sepenuhnya “dipercaya” untuk berdiri memimpin organisasi atau komunitasnya secara absolut.
Pengalaman sewaktu konferensi tingkat provinsi, terulang kembali pada saat kongres nasional yang di dalamnya memiliki hajat pemilihan ketua umum pengurus tingkat nasional. Bagi banyak orang, ini adalah ajang pertemuan sekaligus politik organisasi yang sangat besar. Tidak heran, saya pun terus “diteror” dan “disetir” oleh banyak orang, untuk sekadar bertindak ini dan itu, sebab saya memegang satu suara, yaitu perwakilan badan semi otonom Jakarta Selatan. Pening, muak, menangis, serasa dipenjara, bosan, semua rasa merambah karena saya merasa sebagai ketua tetapi semua orang seperti “menekan” saya. Tetapi pada akhirnya, saya dapat memegang teguh prinsip kebebasan saya hingga akhir pemilihan, meskipun hingga saat ini mungkin beberapa orang menjadi hilang respek bahkan membenci sebab saya tidak mengikuti apa yang mereka katakan dan inginkan - tetapi biarlah. Hidup memang tentang pilihan. Seperti yang banyak orang bilang, bahwa hidup kita tidak akan pernah bisa memuaskan seluruh orang. Menjadi pemimpin itu berat, terlebih perempuan. Banyak stereotip yang menghambat perempuan untuk berkembang.
Salah satu studi menemukan bahwa ketimpangan gender masih sering ditemui. Studi yang dilakukan oleh University of Buffalo School of Management telah menganalisis 136 kasus dengan melibatkan 19 ribu responden, selama 59 tahun belakangan. Peneliti menyimpulkan bahwa ketimpangan gender memang semakin berkurang di beberapa dekade terakhir, tapi bukan berarti benar-benar menghilang. “Alasan utama dibalik langgengnya ketimpangan gender karena tekanan sosial yang menyebabkan perbedaan karakteristik antara perempuan dan laki-laki,” jelas peneliti, dilansir Times of India. Sifat laki-laki yang cenderung tegas dan sifat perempuan yang mengedepankan perasaan dalam stereotip masyarakat membuat laki-laki dianggap lebih mampu menjadi seorang pemimpin dibanding perempuan.
Menurut data PBB 2015, terdapat kesenjangan gender yang nyata ketika membicarakan posisi kepemimpinan laki-laki dan perempuan di berbagai tempat. Saat ini, ada 18 perempuan pemimpin dunia, termasuk 12 perempuan kepala pemerintahan dan 11 perempuan kepala negara terpilih. Perempuan-perempuan ini mengemban hanya satu persepuluh jumlah pemimpin dunia saat ini dari negara-negara anggota PBB.
Oleh karenanya, sebebas-bebasnya sekarang, tetap saja kita masih hidup dalam budaya patriarki. Budaya ini yang mem-framing, membentuk suatu point of view bahwa perempuan haruslah feminim, salah satu sifat feminim ialah mau diatur, mau dipimpin. Berdasarkan hasil penelitian oleh Putri dan Fatmariza (2020) dengan judul “Perempuan dan Kepemimpinan di Organisasi Mahasiswa Universitas Negeri Padang”, memperoleh kesimpulan bahwa hanya 5,88% perempuan yang menjadi pemimpin di Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) sejak 2015-2020. Penyebab rendahnya kepemimpinan perempuan di Ormawa adalah karena perempuan dianggap kurang paham dalam mengambil kebijakan yang mempengaruhi orang banyak dengan persentase sebesar 62%. Sebesar 47% perempuan tidak percaya diri untuk menjadi pemimpin. Sebanyak 44% mengatakan ketidakyakinan kepada perempuan dalam memenuhi tanggung jawab menjadi pemimpin. Budaya patriarki yang masih melekat dalam lingkungan organisasi sebesar 59%. Perempuan dianggap tidak mampu mendisiplinkan orang dewasa terkhusus laki-laki menempati presentase sebanyak 54%. Sebanyak 50% perempuan tidak memiliki relasi yang kuat dalam memperoleh suara untuk memimpin. Nampak jelas, budaya patriarki masih melenggang di dunia mahasiswa sekalipun dalam tubuh organisasi yang “mengaku” menjunjung kesetaraan. Hal-hal tadi adalah faktor struktural yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Selain faktor struktural, ada juga faktor kultural, yakni perempuan masih banyak yang menarik diri dalam partisipasi menjadi seorang pemimpin. Selain hal-hal yang telah disebut, dalil-dalil agama yang dipahami secara tekstual juga mempengaruhi cara pandang ini. Seperti contoh, pemahaman kaku terhadap salat berjamaah (makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan) yang wajib menjadi imam adalah laki-laki. Maka yang wajib memimpin dalam semua lini kehidupan adalah laki-laki dan seterusnya.
Kontruksi sosial yang berkembang di masyarakat semakin memvalidasi bahwa pemimpin itu harus laki-laki, jadi bukan hanya menjadi pemimpinnya yang sulit, namun akses untuk kesana juga sudah susah. Bahkan, Alison Gutterman, CEO dan Presiden Jelmar, memiliki pengalaman diskriminasi dan dianggap tidak mampu memimpin di awal karirnya. Ia merasa sulit mendapatkan rasa hormat ketika menjadi womenpreneur di industri yang didominasi oleh laki-laki.
Sehingga pada akhirnya, keterlambatan atau bahkan ketidakberkembangan kaum perempuan di ranah publik, bukan lagi tentang kurangnya kualitas dari perempuan itu sendiri, melainkan stereotip yang terlanjur berkembang dan menjadi atmosfer yang menekan kaum perempuan dari banyak sudut. Maka, Semakin banyak perempuan yang berani dan berhasil tampil di muka umum akan sangat berpengaruh mengikis stigma yang selama ini mengungkung. Setidaknya, lambat laun langkah ini mampu mengembalikan kedudukan perempuan sebagai manusia, makhluk Tuhan yang diciptakan dan berkesempatan menjadi pemimpin di muka bumi.
Artikel ini bersumber dari https://www.jurnalperempuan.org/blog-sjp/stereotip-gender-dan-subordinasi-terhadap-kepemimpinan-perempuan
-
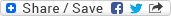
- Log in to post comments